“Saya tidak berafiliasi dengan madzhab atau organisasi manapun” lantang seorang yang mengaku dirinya Guru. Ironi memang, pada saat yang bersamaan ia sendiri tidak mampu memahami Al-Qur’an dan hadis Nabi secara mandiri, alih-alih bertanya atau mengambil pemahaman dari ahli.
Adalah KH. Ahmad Dahlan Termas, ia menulis kitab khusus guna menanggapi marakanya perdebatan tajdid dan purifikasi ajaran pada masa itu. (h.53). Mula-mula beliau menjabarkan keharusan taqlid bagi muslim yang tidak memiliki kemampuan berijtihad. Khususnya imitasi dalam soal furu’.[1] (h.56-58)
Bukan tanpa dasar, keharusan taqlid adalah bagian dari perintah Tuhan sebagaimana dalam ayat ke 43 Surat An Nahl “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” Sebagaimana penafsiran Al- Qurthubi, ayat ini memberi penegasan, bahwa masyarakat awam harus bertaqlid pada para ahli (ulama).[2]
Konon, madzhab dalam fikih tidak terhitung jumlahnya, seiring berjalannya waktu, regulasi bermadzhab perlu ditetapkan, kriteria madzhab perlu dispesifikasikan, lantas menyisakan empat madzhab utama yang kita kenal hari ini (Maliki, Hanafi, Syafi’i dan Hambali). Kemudian ditetapkanlah larangan imitasi pada selain madzhab empat. (h. 69-72)
Mengapa perlu ada pembatasan? Kiai yang ahli dalam ilmu falak ini memahami betul kegelisahan pembaca setelah ia mengutip larangan bertaqlid kepada mazhab di luar empat mazhab yang muktabar. Karena itu, ia memberikan beberapa alasan sebagai penjelas. Di antara yang paling penting dan rasional adalah kenyataan bahwa mazhab selain empat tidak memiliki dokumentasi dan rantai transmisi keilmuan yang utuh. Akibatnya, orisinalitas pendapat yang dinisbatkan kepada imam-imamnya tidak dapat dipastikan. (h.75)
Setelah pemilik empat madzhab ini wafat, corak pergerakan para murid terfokuskan setidaknya pada dua hal . Pertama, tadwin (kodifikasi), rumusan hukum imam madzhab diabadikan dalam bentuk karya tulis. Muhammad bin Al Hasan misalnya, ia berhasil menghimpun madzhab Imam Abu Hanifah. Al Mughni memuat fatwa dan rumusun hukum Imam Ahmad bin Hanbal, buku 12 Jilid ini ditulis oleh Ibnu Qudamah. Kedua, para murid menjadikan rumusan hukum serta metode yang dilakukan imam sebagai standar dalam menjawab persoalan yang dijumpai atau biasa disebut takhrij al Fiqh.[3]
Lantas bolehkah beramal dan berfatwa menggunakan pendapat dho’if?, Kapan qoul ulama diklaim dho’if? Untuk menemukan jawaban keresahan diatas, kiranya perlu kita memahami tulisan Kiai Dahlan dengan sub “Jawaz al ‘Amal bil Qoul al Dho’if li al Nafsi la li al Ghoir wa la li al Ifta’”. (h.105)
Siapa sebetulnya pemilik otoritas berfatwa? Mengutip Raudhat al Tholibhin Kiai Dahlan menegaskan bahwa “siapapun yang belum sampai pada derajat “boleh berfatwa” tidak boleh memberikan jawaban keagaman kecuali dalam persoalan yang sudah jamak diketahui, seperti kewajiban niat dalam wudhu’, kesunahan witir dan sejenisnya. (h.110) Beliau kemudian menghadirkan teladan ulama-ulama awal yang sering memilih menjawab “tidak tahu” sebagai bentuk kehati-hatian (warā‘) demi menjaga agama dari kesembronoan pribadi. (h.112)
Pun demikian, sebagian besar penjelasan krusial dalam bermadzhab tidak betul-betul menjadi “jelas” . pada sub marotib al ulama’ (jenjang keulamaan) penulis belum sempat mendefinisikan mujtahid mustaqil, mujtahid muntasib dan seterusnya. Atau pada saat beliau melarang talfiq, pembaca tidak memiliki ketentuan khusus dalam memaknai apa itu talfiq. Sehingga kaburnya makna seringkali dialami. Boleh jadi pasar penulis bukan masyarakat awam seawam-awamnya. Sebagaimana disampaikan pada bagian awal, kitab ini dilatar belakangi fenomena tajdid dan purifikasi ajaran pada era beliau. Sekian.
Hari ini, kita menjumpai gerakan tajdid dan purifikasi keagamaan begitu massif, mengajak kembali kepada Al-Qur’an dan Hadits. Paradoks ini akan terus berlangsung selama masih marak (dan akan terus begitu) anggapan bahwa bertaqlid pada ulama tertentu adalah bagian dari kemunduran beragama. Alkisah, Rasulullah sangat marah terhadap sekelompok orang yang berani mengeluarkan putusan hukum tanpa kompetensi. Kejadian itu bermula ketika salah seorang pasukan perang mengalami luka di kepala dan dalam keadaan junub. Ia pun dilanda dilema: apakah harus mandi besar atau menunggu lukanya mengering terlebih dahulu. Ia kemudian bertanya kepada beberapa rekannya. Tanpa pengetahuan yang memadai, mereka menjawab bahwa ia tetap wajib mandi.
Akhirnya ia mandi besar sebagaimana yang disarankan, tetapi nahas, bukannya sembuh, ia justru wafat karena luka itu semakin parah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi, beliau sangat murka seraya bersabda: “Mereka telah membunuhnya. Allah akan membalas perbuatan mereka. Jika mereka tidak tahu, bukankah seharusnya mereka bertanya? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya.”[4]
Kesimpulan
Ibarat oase di gurun sahara, Fathul Majid-dengan segala kekurangan yang mungkin dimilikinya-hadir sebagai jawaban atas geger gedennya klaim beberapa pihak, vonis paling paham agama, vonis paling modern dan vonis-vonis tidak berlandaskan lainnya. Kendati agama adalah milik semua pemeluknya, ia tidak lantas boleh dibongkar-pasang oleh selain ahlinya. Terakhir, kedepan semoga akan bermunculan kitab-kitab dengan tema yang sama dalam perspektif berbeda. Semoga.
***
Catatan kaki:
- Furu’ adalah hukum yang dihasilkan oleh dalil-dalil asumtif (dzanni) atau tidak ada dalil atasnya secara eksplisit. furu‘ inilah yang dinamakan fikih karena proses pengambilannya dengan jalan ijtihad. seperti wajibnya niat dalam wudlu, membaca fatihah dalam salat, sunah witir, niat malam hari syarat puasa ramadan, wajib zakat pada harta anak kecil, tidak wajib zakat pada hiasan yang diperbolehkan, membunuh dengan benda tajam dan berat mewajibkan qishas dan lain-lain (lihat dalam Sayyid Muḥammad bin ‘Alawī al-Mālikī al-Ḥasanī, Syarḥ Manẓūmat al- Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011, pembahasan al-fiqh)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurthubi, Al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, Vol. 11, ed. Ahmad al- Barduni dan Ibrahim Ath-Fayish (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, cet. ke-2, 1384 H/1964 M), hlm. 272.
- Kholid Musaid ar-Ruwaiti, At-Tamadzhub: Dirasah Nadzariyah Naqdiyah, cet. ke-2, vol. 2 (Riyadh: Dar at- Tadmuriyyah, 2013), 655.
- HR. Abu Daud: 336






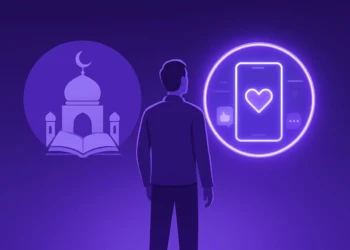






Discussion about this post