Al-Qur’an merupakan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam untuk ummat Islam. Meskipun hampir 1400 tahun diturunkan, makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an tentulah masih relevan untuk diaplikasikan dalam berbagai perkembangan zaman. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab suci yang orisinalitasnya tetap terjaga.
Dalam perjalanannya, Al-Qur’an ditafsirkan dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa, agar memudahkan setiap pembacanya mendalami makna yang terkandung pada Al-Qur’an. Upaya penerjemahan dan penafsiran ke dalam bahasa daerah pun tak luput menjadi usaha ulama’ Nusantara guna menyuguhkan makna yang mudah dipahami oleh kalangan awam.
Adalah KH. Bisri Musthofa dengan tafsirnya Al-Ibriz dan saudaranya KH. Misbah Musthofa dengan tafsirnya Al-Iklil. Kedua bersaudara ini sama-sama berasal dari Rembang, Jawa Tengah dan sama-sama menulis sebuah tafsir Al-Qur’an serta sama-sama produktif dalam dunia kepenulisan.
Meskipun tafsir yang beliau berdua tulis menggunakan bahasa Jawa, namun terdapat perbedaan menarik dalam hal pemaparannya yang akan penulis ungkap dalam artikel ini dan sample sederhana yang digunakan dalam pembahasan ini adalah tafsir surah Al-Fatihah.
Jika Kiai Bisri dalam muqoddimah Al-Ibriz menyampaikan bahwa tafsir yang beliau tulis penggunaan bahasanya ditulis secara lugas dan sederhana, namun saudaranya Kiai Misbah dalam Al-Iklil memberikan pemaparan keterangan yang lebih luas lagi, seperti di ayat pertama dalam lafadz basmalah. Jika dalam tafsir Al-Ibriz ayat tersebut tidak dijabarkan secara mendalam, maka pada tafsir Al-Iklil, Kiai Misbah menjelaskan sebagaimana berikut :
“Ucapan Bismillah iki suwijine pernyataan saking kula yen dewek’e muji-muji marang Allah lan pernyataan muji-muji kang mengkono iku kulo biso ngelakoni sebab berkahe Allah kang Moho Luhur lan Moho Asih.” (Ucapan Bismillah ini merupakan suatu pernyataan dari saya jika Allah memuji kepada diri Nya dan pernyataan pujian yang demikian itu saya bisa melakukan sesuatu karena sebab berkahnya Allah yang Maha Luhur dan Maha Penyayang). Selain itu, dalam tafsir ini Kiai Misbah juga menjabarkan hukum membaca basmalah pada surah Al-Fatihah ketika shalat menurut pendapat madzhab Syafi’i.[1]
Kemudian dalam Tafsir Al-Ibriz, Kiai Bisri meringkas penafsiran ayat 2- 4 pada surah Al-Fatihah sebagai berikut:
“Sekabehane pengalem iku namung kagungane Allah Ta’alaa dewe kang mengerani lan nguwasani alam kabeh iki. Gusti Allah iku persifatan welas asih marang sekabehane makhluk. Uga Allah Ta’alaa persifatan kang Mengerani dino kiamat. Kuoso ganjar marang wong-wong kang podho taat lan kuoso nyikso marang wong-wong kang podo nulayani perintahe Gusti Allah Ta’alaa.” (Keseluruhan pujian itu hanya milinya Allah Ta’alaa sendiri Dzat yang menuhankan dan Dzat yang menguasai semua alam ini. Allah itu memiliki sifat kasih sayang kepada semua makhluk dan Allah Ta’alaa memiliki sifat yang menguasai hari kiamat. Memiliki kuasa untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang pada taat dan memiliki kuasa untuk memberikan siksaan kepada orang-orang yang telah melanggar perintahnya Allah Ta’alaa).[2]
Namun dalam tafsir Al-Iklil, Kiai Misbah menjelaskan secara panjang lebar mengenai macam-macam pujian yang terdiri atas 4 macam puji (pada ayat 2), kemudian beliau juga memberikan tambahan keterangan dari Syaikh Wahab bin Munabbih, “Allah Ta’alaa iku gawe alam kabehe 18. 000 alam. Alam dunyo iki siji setengah sangking alam kang 18. 000 iki kaya alam jin, alam malaikat, alam hayawan, alame tanduran lan sak piturute” (Allah Ta’alaa itu membuat seluruh alam jumlahnya 18. 000. Alam dunia ini termasuk salah satu dari 18. 000 alam ini, selain itu ada alam jin, alam malaikat, alam hewan, alam tumbuhan dll).
Lalu makna Rabb Al-Alaamin menurut Kiai Misbah dapat juga dimaknai dengan perasaan takut sekali kepada Allah sebagai Dzat yang menguasai seluruh alam dan dapat menjadikan seseorang bisa fakir bisa kaya begitupun sebaliknya. Atau membuat seseorang bisa Islam bisa kafir begitupun dengan sebaliknya.[3]
Masih dalam Al-Iklil pada keterangan ayat berikutnya, yakni ayat ketiga. Karena Allah yang menguasai alam seisinya, maka dalam ayat ini Kiai Misbah memaparkan korelasinya dengan ayat sebelumnya sebagai berikut: “Nanging disusuli dawuh Rahman Rahim iku perlune supoyo iku anggrengseng marang rahmate Allah” (Lalu diteruskan dengan ayat Rahman Rahim itu diperlukan supaya seseorang itu dapat merasakan rahmat-Nya Allah).
Pada pemaparan ayat keempat Kiai Misbah selain menjelaskan kedudukan Allah sebagai Tuhan yang Merajai Hari Akhir, dijabarkan pula bahwa dalam pendapat ulama ahli qiroat bahwa ayat ini dapat dibaca Maaliki Yaum Ad-Diin dengan memanjangkan atau menambahkan alif setelah mim atau dapat dibaca Maliki Yaum Ad-Diin dengan tidak memanjangkan atau menambahkan alif karena maknanya sama-sama menguasai atau merajai.
Kemudian di ayat kelima pada tafsir Al-Ibriz Kiai Bisri menjabarkan demikian: “Lan ugo tansah nyuwun supoyo Allah Ta’alaa paring dalan kang lurus (lan) kang biso nekaaken marang kebahagiaan dunyo lan akhirat” (dan juga selalu memohon supaya Allah Ta’alaa memberikan jalan yang lurus (dan) yang dapat mendatangkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat).
Namun ketika kita membaca dalam tafsir Al-Iklil, maka dalam hal ini Kiai Misbah menjabarkan secara panjang lebar mengenai tiga tingkatan ibadah seorang hamba berdasarkan maqam/kedudukannya, yakni yang pertama tingkat rendah. Dimana ibadah ini dilakukan oleh seorang hamba karena mengharapkan pahala dan takut akan siksa Nya Allah, kemudian di tingkatan kedua yakni ibadahnya golongan tengah. Dimana seorang hamba melaksanakan ibadah karena ingin mulia atau ingin dikatakan dekat kepada Allah. Adapun ibadah tingkatan ketiga yakni ibadahnya orang luhur. Dimana seorang hamba beribadah kepada Allah karena memang waktunya untuk berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah dan dia paham akan hak-nya sebagai seorang hamba untuk selalu mengkoneksikan dirinya dengan Allah sebagai Tuhannya.[4]
Adapun dalam ayat keenam dan ketujuh, Kiai Bisri dalam Al-Ibriz memaparkan penafsiran sebagai berikut, “Lan ugo tansah nyuwun supoyo Allah Ta’alaa paring dalan kang lurus, kang biso nekaaken marang kebahagiaan dunyo lan akhirat. Dedalan wong kang dihin-dihin kang wes podo keparing nikmat, dudu dedalan kang diambah wong-wong kang keno bendhu lan wong-wong kang keno sasar.” (Dan juga selalu memohon supaya Allah Ta’alaa memberikan jalan yang lurus, yang dapat mendatangkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan orang terdahulu yang sudah mendaoatkan nikmat, bukan jalan yang dituju orang yang mendapat murka Allah dan orang yang disesatkan oleh Allah).
Sedangkan Kiai Misbah dalam Al-Iklil memberikan penafsiran bahwasannya kalimat “ihdi” memiliki makna memohon hidayah kepada Allah yang dalam artian meskipun manusia dapat memberikan petunjuk kebenaran, namun yang dapat menggerakkan hati seseorang melakukan ketaatan hanyalah Allah Ta’alaa. Maka sebagai keringkasannya, Kiai Misbah memaparkan bahwa ayat keenam ini memiliki makna agar ummat Islam selalu meningkatkan ketaatan dengan mempelajari ilmu agama dan mengamalkannya.
Adapun shiratal mustaqim yang dimaksud disini yakni agama Islam, sementara makna an’amta alaihim pada ayat ketujuh memiliki makna jalan yang ditempuh oleh para Nabi, para Rasul, dan kaum Sholihin. Kemudian dalam lafadz maghdu bi alaihim (golongan yang dimurkai oleh Allah) merujuk kepada orang Yahudi, mereka diberi petunjuk kebenaran dan banyak para Nabi dan Rasul diutus atasnya, namun mereka enggan untuk melaksanakan kebenaran tersebut.
Lalu lafadz dhallin (golongan yang tersesat) merujuk kepada orang Nasrani yang tersesat dan menyelewengkan jalan kebenaran agama yang semula monotheisme lalu konsepnya menjadi trinitas. Waba’du, demikian seklumit penafsiran surah Al-Fatihah dalam perspektif dua tafsir karya Ulama’ Nusantara tersebut. Wallahu A’lam..
***
[1] Misbah Musthofa, Al Iklil Fii Ma’ani Tanzil, ( Surabaya : Percetakan Al-Ihsan, tt), Vol. 1, h. 2.
[2] Bisri Musthofa, Al Ibriz lii Ma’rifatil Qur’an Al Aziz, (Kudus : Percetakan Menara Kudus, tt), Vol. 1, h. 3.
[3] Misbah Musthofa, Al Iklil Fii Ma’ani Tanzil, ( Surabaya : Percetakan Al-Ihsan, tt), Vol. 1, h. 4.
[4] Ibid, h. 5.

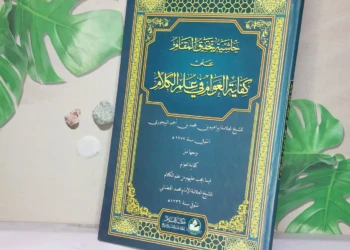
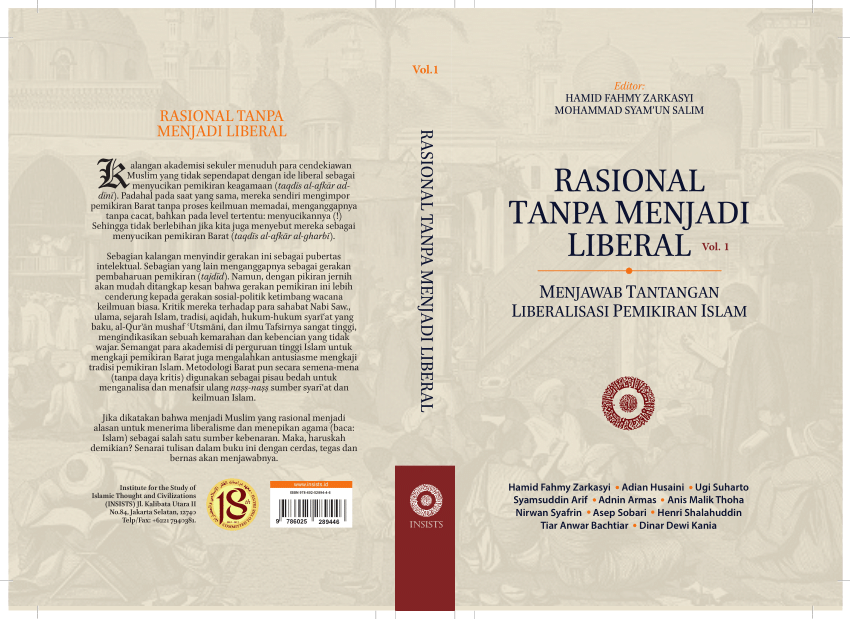
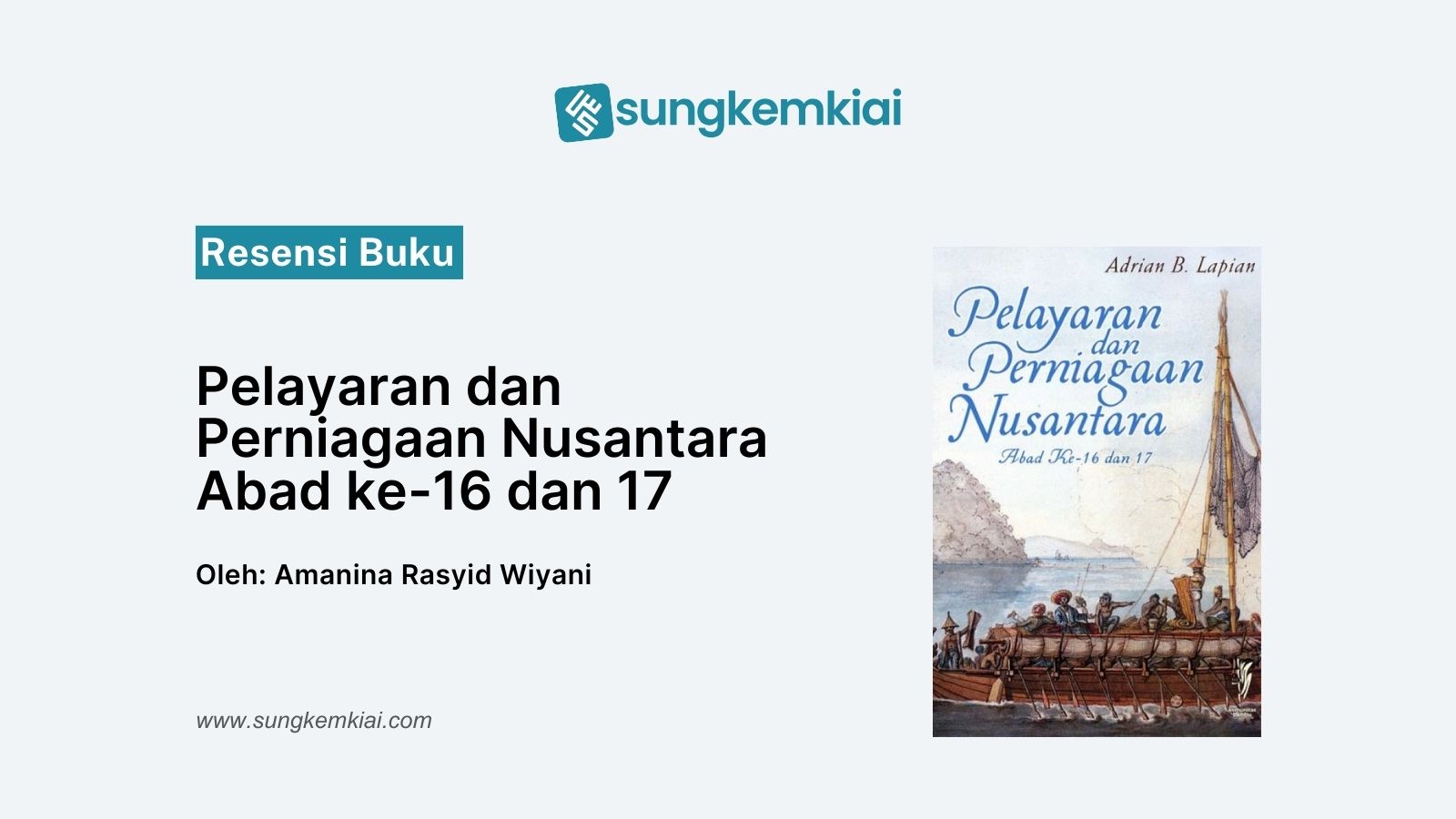

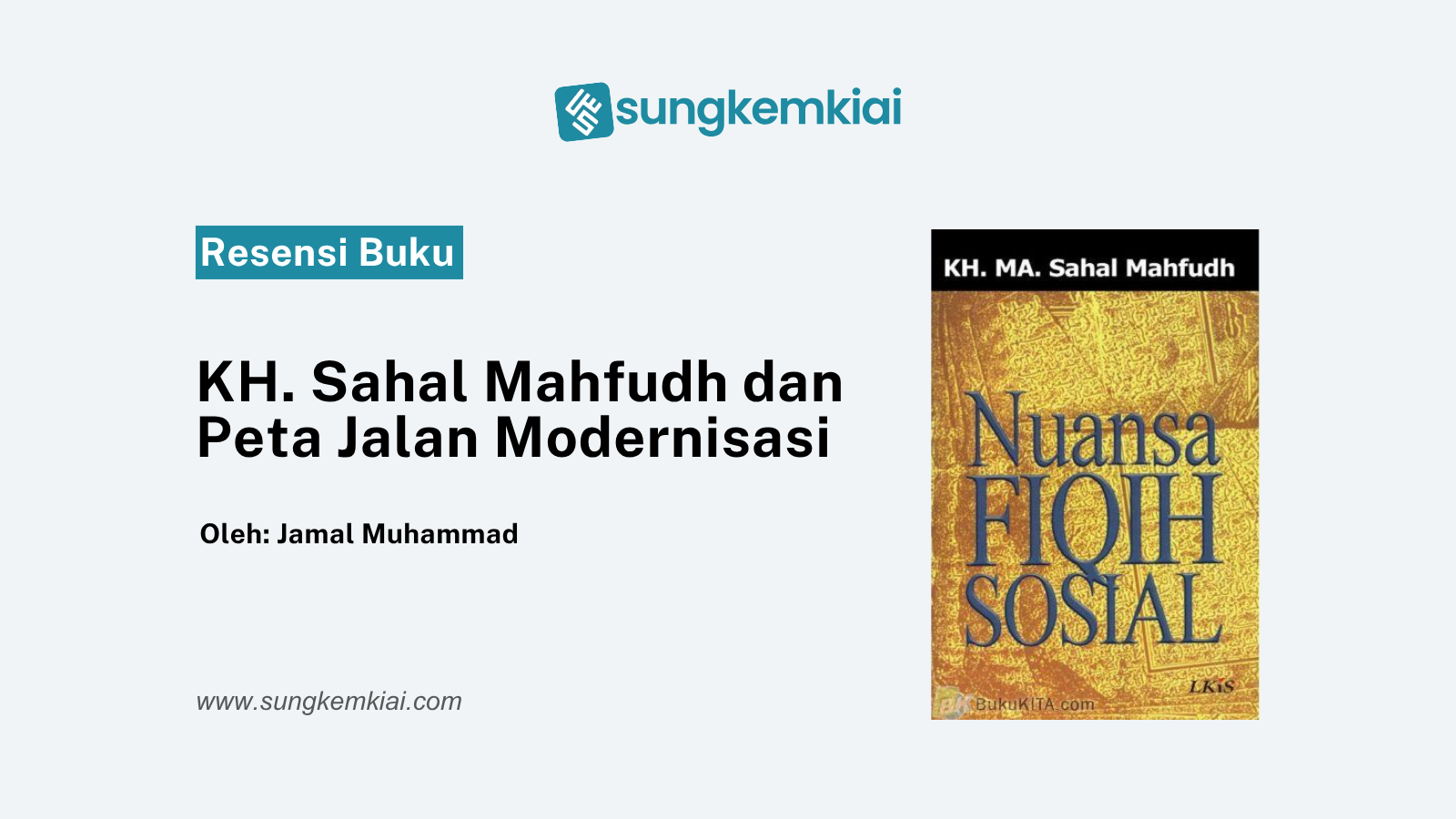
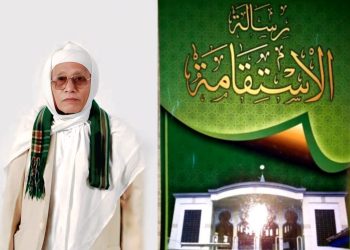
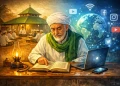





Discussion about this post