Ketika kata “filsafat” terdengar, pastilah peradaban Yunani kuno yang pertama kali tergambar dalam pikiran kita. Padahal, setiap peradaban, wilayah, dan kelompok memiliki falsafahnya sendiri sebagai prinsip pembimbing dalam kehidupan mereka, termasuk Jawa.
Meminjam Alegori Goa milik Plato, filsafat bisa diintuisikan sebagai proses abstraksi yang bertolak dari realitas untuk kembali (guna mencerahkan) realitas. Filsafat adalah upaya bangkit dari bawah, dunia bayang-bayang yang gelap di dasar goa, menuju mulut goa untuk keluar, dan pada akhirnya turun lagi ke dasar goa.
Sehingga, dalam usaha memahami apa yang disebut dengan “filsafat Jawa”, kita harus menerapkan langkah-langkah di atas: keluar dari realitas asal, dan kembali lagi. Realitas asal adalah rakyat – entah dalam arti penderitaan, kebahagiaan, atau apa pun itu yang mencirikan sifat ke-“rakyatan”-nya.
Untuk memperjelas apa yang saya katakan di atas, mari kita kembali menengok dua kisah klasik Jawa yang berasal dari abad ke-15 atau ke-16: Kentut Semar dan Bima Suci (Nawaruci).
Dalam Kentut Semar dikisahkan, ketika Semar marah, alih-alih mengambil gada, keris, atau senjata-senjata dalam wayang pada umumnya, ia lebih memilih kentut sebagai senjata pamungkas. Kentut milik Semar ini jelas bukan senjata yang membinasakan musuh-musuhnya, ia hanya membuat semua musuhnya kalah dan takluk di hadapannya.
Menurut Armada Riyanto, kentut ini menjadi solusi khas Semar dalam menyelesaikan segala bentuk persoalan, konflik, dan perang. Seakan-akan Semar hendak berpesan kepada kita bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Harus ada cara lain yang tidak membinasakan dan memunahkan, tetapi yang mengingatkan, yang membuat orang kembali pada jati diri dan jalan yang benar. Kentut tidak akan membunuh orang, tetapi ia membuat orang sadar dengan jati dirinya, ketika sebelumnya ia dilupakan oleh segala bentuk kemerlap duniawi.
Kisah Kentut Semar nampaknya merupakan salah satu yang membentuk paradigma dan karakter masyarakat Jawa yang anti terhadap cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan sebuah persoalan maupun konflik, dan cenderung memilih cara-cara yang mengarah pada usaha mengingatkan: “ngilingake.”
Tak kalah menarik dengan kisah Kentut Semar, kisah Bima Suci juga memiliki arti yang sangat mendalam bagi khazanah kefilsafatan Jawa. Bima Suci bercerita tentang pengalaman akan Allah dan suka duka dalam pencarian air kebijaksanaan. Namun, yang unik dan paradoks dalam kisah Bima adalah ketika ia, yang memiliki postur tinggi dan besar, harus masuk ke telinga Dewa Ruci yang badannya kecil. Tidak ada cara lain kecuali dengan “menghilangkan diri.” Hingga pada akhirnya, dengan cara ini, Bima bisa mencapai pengenalan diri sejati (true self) dan ketenangan sejati.
Dari kisah Bima Suci bisa disimpulkan bahwa dalam khazanah Jawa, usaha memperoleh kebijaksanaan nampaknya merupakan proses yang saling bertentangan. Semar juga digambarkan sebagai sosok yang paradoksal. Di satu sisi, ia adalah manusia biasa, namun di sisi lain, ia memiliki sisi keilahian atau lebih tepatnya sebagai perwujudan dari dewa.
Filsafat Jawa yang paradoks ini juga terbukti dari beberapa ungkapan yang sangat populer di Jawa, seperti menang tanpa ngasorake, ngluruk tanpa bala, dan ngono ya ngono ning aja ngono.
Pasti kita bertanya-tanya, mengapa filsafat Jawa menempatkan kebijaksanaan pada pertentangan? Lilo Sunaryo melihat filsafat Jawa memiliki orientasi yang sama sekali berbeda dengan filsafat Yunani maupun Modern. Ketika hampir semua aliran filsafat berfokus untuk menemukan kebenaran atau kebahagiaan hakiki, filsafat Jawa mengabaikan itu semua.
Kebijaksanaan tidak diartikan sebagai kebenaran atau kebahagiaan hakiki. Kebijaksanaan, dalam kacamata filsafat Jawa, adalah “ketenteraman,” tidak lebih. Kebijaksanaan ini tidak bisa diperoleh dengan dialektika ala Hegel, skeptisismenya R. Descartes, atau observasi dan eksperimennya para saintis modern. Ia hanya bisa diperoleh dengan “rasa” yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret “laku.” “Rasa” bukanlah konsep yang menuntut adanya penjelasan, ia hanya bisa dipahami jika kita menjalankannya. Sebagaimana Suryomentaram yang menolak adanya konseptualisasi dari “rasa.”
Pada akhirnya, semua khazanah Jawa bermuara pada ungkapan “ngelmu kelakone kanti laku.” Dalam proses ini, rasio tidak mendapatkan tempat prioritas karena proses ini hanya bisa dipahami tatkala dijalani secara eksistensial lewat laku dan pengalaman yang bersifat transendental.

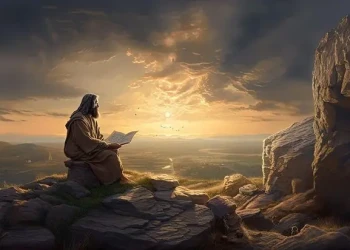


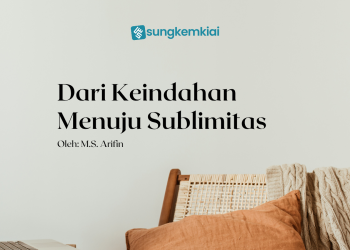








Discussion about this post