Bertahun-tahun sebelum membaca novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway, saya merasa bahagia disamping cemas melanda setiap kali menyaksikan laut. Bahagia karena laut adalah sumber mata pencarian, cemas karena laut juga bisa murka menenggelamkan siapa saja. Di tengah laut itu ada para nelayan yang bertaruh nyawa sedang mengadu nasib di atas air yang berombak ganas.
Ketika nanti beranjak dewasa ada banyak pelajaran penting saya dapatkan dari sana bahwa laut dan para nelayan adalah sumber nilai kisah kehidupan.
***
Sore itu, di gubuk bambu menghadap laut, angin berembus kencang dari arah selatan, saya dan bapak duduk-duduk berdua saja menyaksikan laut sambil mencicipi es cendol. Itu momen tahun 2009 sebelum saya mondok dan akan mondok pada tahun 2011. Itu ketika kami liburan berdua saja, ketika kali pertama bapak baru membeli sepeda motor Bravo bekas, ketika saya masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar—momen haru setelah nenek meninggal, ibu kandung bapak.
Saya tidak tahu persis obrolan tentang apa saja dengan bapak pada waktu yang kini telah kami lewati bersama.
Tetapi saya masih ingat bahwa waktu itu saya berpikir laut dan para nelayan adalah sumber kisah kehidupan. Namun saya tidak tahu persis mengapa saya berpikiran begitu dulu. Pikiran saya selalu mogok jika diajak berkelana jauh sebab saya baru bisa membaca dan belum gemar membaca.
Baru kemudian aktif membaca buku setelah masuk kampus.
***
Bertahun-tahun kemudian saya membaca novel Lelaki Tua dan Laut karya Ernest Hemingway ketika duduk di bangku kampus. Novel itu memukau sekali. Saya melahap novel itu pertama kali di IPUSNAS dalam sekali duduk dan membacanya berulang-ulang tanpa rasa bosan.
Saya memburu novel bermutu itu; sebab berkualitas.
Kalau ada mahasiswa bertanya pada saya bacaan apa yang bagus bagi pembaca pemula, saya selalu merekomendasikan novel tak lekang zaman itu.
Novel itu mengisahkan hidup Santiago, lelaki tua kurus kering dan pucat dengan kulit keriput berkerut merut di tengkuknya. Lelaki tua itu memancing ikan di tengah laut selama delapan puluh empat hari tetapi gagal menangkap seekor ikan. Ia ditemani seorang anak lelaki bernama Manolin selama empat puluh hari pertama dan empat puluh hari berikutnya lelaki tua itu tetap tidak berhasil mendapat seekor ikan pun.
Tahu lelaki tua itu membawa tangkapan kosong, orangtua Manolin tidak membolehkan anaknya bergabung melaut bersama lelaki tua itu lagi; sebab dia pembawa sial, katanya. Tetapi lelaki tua itu tidak menyesal, justru tetap menampakkan sikap kasih sayang pada anak lelaki tersebut.
Namun semangatnya tak pernah luntur—sekali pun tetap tak berhasil mendapat seekor ikan, sekali pun di tengah laut hanya seorang diri.
Lelaki tua itu mencoba kembali melaut.
Di tengah lautan yang ganas itulah Santiago berjuang dan bertarung mati-matian dengan seekor ikan marlin yang berukuran besar. Hanya seorang diri.
Kita sebagai pembaca dibawa pada sifat karakter manusia tangguh, gigih, dan berjiwa kesatria dalam diri Santiago menghadapi pertarungan hebat melawan ikan besar.
Lelaki tua itu pantang menyerah meski dirinya telah dihancurkan, tetapi tidak bisa dikalahkan oleh seekor ikan sekalipun besar. “Ada banyak cara membereskan pekerjaan,” katanya, “termasuk menangkap seekor ikan berukuran besar.”
Ketika membaca novel itu jiwa saya bergemuruh hebat—seolah saya benar-benar berada di tengah laut dan menjelma diri seorang Santiago dalam menghadapi kehidupan ini.
***
Kita bisa membaca Santiago, Laut, dan Seekor Ikan besar menjelma apa saja.
Jika kau seorang politisi, kau bisa menjadi Santiago yang memberantas korupsi. Anggaplah para koruptor itu adalah ikan-ikan ganas yang memancing keributan di tengah laut atau negara ini. Jika kau seorang mahasiswa, kau juga bisa menjadi Santiago yang mematahkan argumen dosen anda dengan cara-cara elegan. Atau kau seorang aktivis. Menjadi Santiago yang pantang menyerah dalam situasi menekan dan mengusik naluri karena ada sogokan dari pimpinan kampus adalah prinsip yang semestinya ditanamkan dalam diri setiap aktivis.
Tapi kalau saya membayangkan Santiago adalah bapak saya sendiri. Ia seorang buruh tani. Dan saya pikir bapak punya karakter mirip dengan Santiago, sementara saya adalah Manolin yang sesekali membantunya jika ada pekerjaan merawat sawah milik orang di tengah terik matahari yang menyengat punggung.
Atau saya membayangkan seekor ikan besar itu adalah perempuan yang tak mudah saya tak taklukkan yang menusuk-nusuk hati, dan saya tak mungkin menyerah sebelum tersiksa oleh kenyataan pahit, aih.
***
Kini saya membayangkan laut adalah panggung kehidupan. Kita adalah para nelayan yang mempertaruhkan nyawa demi bertemu kembali dengan keluarga.
Suatu hari nanti, ketika saya diberi kesempatan mendidik anak, saya punya impian akan mengajak anak saya menyaksikan laut—seperti dahulu bapak mengajari saya untuk merenungi laut. Di situ anak saya akan belajar tentang apa saja tanpa rasa takut dan cemas akan pertarungan hidup dan mati demi keluarga.

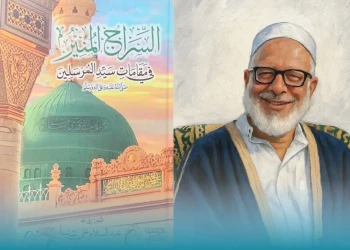

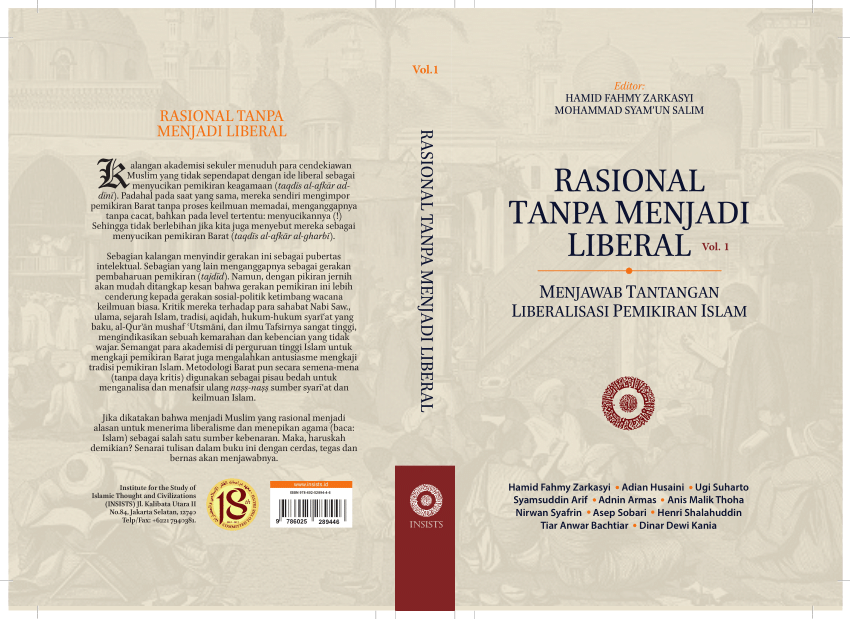
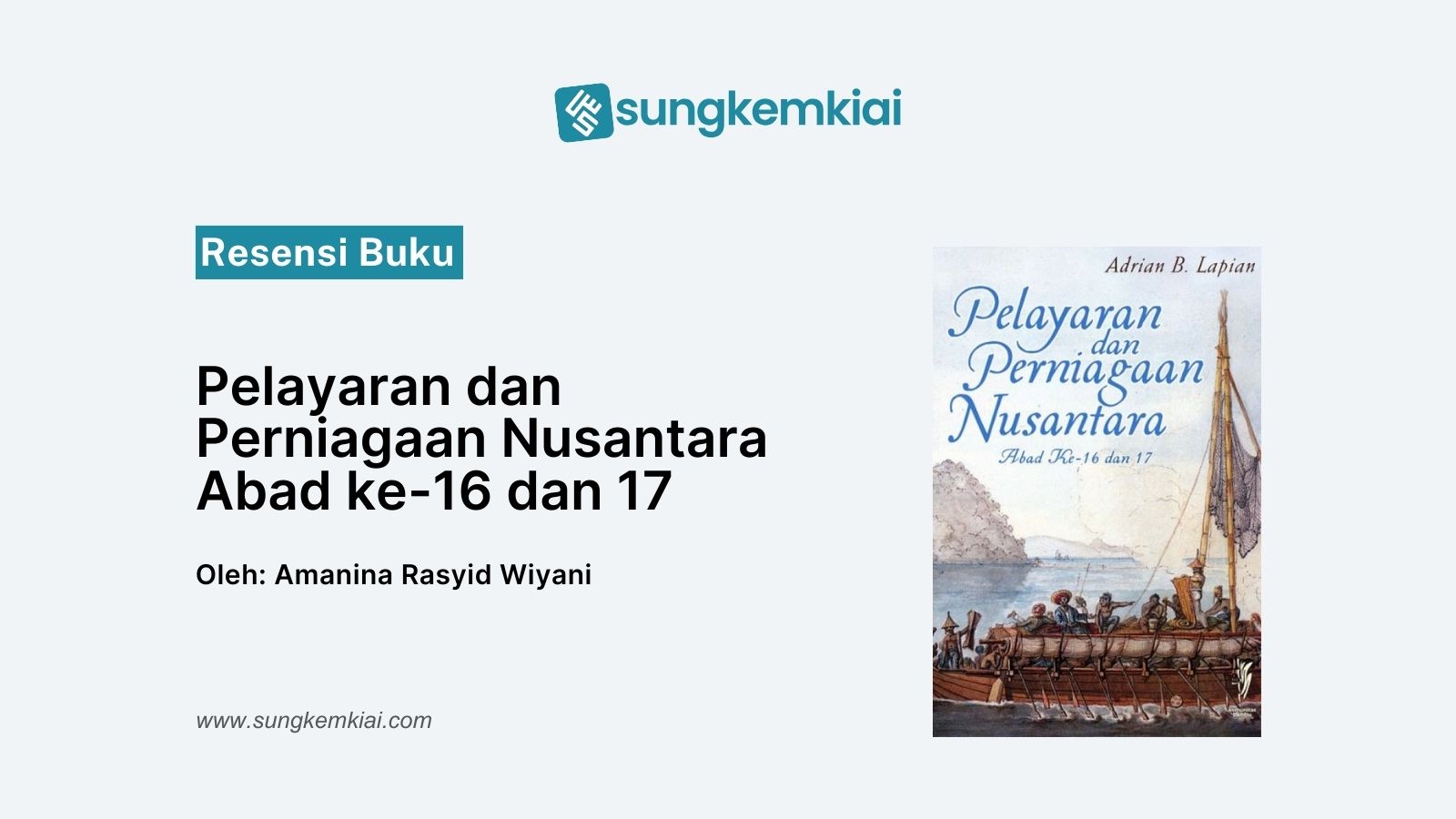








Discussion about this post