Jika Anda bertanya buku apa yang bagus namun ringan dibaca dan menawarkan perspektif menarik dan mendalam tentang suatu hal tetapi tidak membosankan dibaca dalam mengisi waktu senggang, maka jawabannya adalah buku-buku karya Emha Ainun Nadjib. Atau sapaan yang biasa dikenal Cak Nun.
Dalam sekian banyak karyanya, Cak Nun selalu menghadirkan sesuatu yang bikin pembaca berpikir dan berkontemplasi atas sejumlah esai-esai pendeknya; yang panjangnya dalam buku ini hanya dua halaman, tidak lebih.
Meskipun karya itu panjangnya hanya dua halaman dan ditulis secara populer seperti layaknya sebuah status di Facebook namun cukup berbobot menandingi karangan kaum elite. Itu terlihat sekali pada pemilihan kalimat-kalimat dan cara-cara berpikir dalam menggandeng kita melalui kisah Markesot untuk memiliki jati diri sebagai seorang pembelajar.
Buku itu setebal 216 halaman dan dibagi ke dalam 8 bagian. Pada tiap-tiap bagian memuat tema-tema tertentu. Penulisan dan penyajian esai-esai dalam buku itu dialogis-dialektis-reflektif; terkadang juga agak humoris, seolah pembaca diajak ngobrol bersama mengenai tema tertentu dengan suasana santai bahagia. Buku itu memuat perbincangan mengarah pada soal keagamaan dalam perkumpulan pengajian yang membahas mengenai tafsir Al-Quran.
Kita akan lihat bagaimana Cak Nun dalam salah satu esainya yang pendek itu mengangkat hal-hal sederhana (dan juga tak sesederhana itu) lalu diolah dan disorot sedemikian rupa dengan perspektif segar dan sejuk membuat kita sebagai pembaca merenung.
Suatu kali Tarmihim, Sundusin, Brakodin memiliki pikiran titik berat masing-masing dalam memahami firman di Surah An-Nahl: 125. Kita kutip perkumpulan orang-orang yang menganggap dirinya orang-orang biasa itu dalam dialog menarik berikut:
“Al-Quran bukan buku pelajaran sekolah, bukan kepustakaan akademik di universitas, juga bukan buku modern kaum cendekiawan turunan pola filosofi dan manajemen ilmu Yunani kuno,” kata Markesot. “Teman-teman di sekitar saya dan anak cucu sampai generasi kelak di kejauhan waktu akan terus mengalami kehidupan yang ganjil sehingga pelatihan utama mereka adalah berpikir genap…”
“Belum pernah mendengar yang ini saya, Cak,” kata Tarmihim.
“Hidup ini penuh keganjilan maka harus dilayani dengan kebiasaan berpikir yang genap …”
“Hidup ini ganjil bagaimana?” Sundusin menyusul bertanya.
“Dengan kegenapan pikiran dan ilmu saja tidak mudah mengurusi ganjilnya kehidupan, apalagi kalau pikiran kita sendiri ganjil. Seluruh pengetahuan dan ilmu kita hanya ganjil, sedangkan yang tidak kita ketahui, yang volumenya jauh lebih besar, adalah kegaiban yang menggenapinya.”
“Agak retak kepala saya,” sahut Brakodin.
“Karena pencipta semua ini sendiri adalah Sang Mahaganjil. Satu. Tunggal. Ahad. Namun, ganjilnya Ahad adalah segenap-genapnya kegenapan. Allah itu Mahaganjil karena Mahagenap. Allah itu Mahagenap maka terasa ganjil pada terbatasnya penglihatan dan penghayatan manusia. Sudahlah, pokoknya selalu teguhkan ‘Qul huwallahu ahad‘…”
Lihatlah bagaimana Cak Nun menyajikan sebuah percakapan bermutu dalam penggunaan kalimatnya sehari-hari yang terasa ringan dan enak dibaca sehingga kita sebagai manusia biasa dituntut secara halus oleh Cak Nun terus berpikir dan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tanpa pernah sekalipun merasa paling benar di antara kemungkinan kebenaran yang ada terhadap penafsirannya sendiri soal Tuhan.
Saya jadi menebak-nebak, jangan-jangan yang dimaksud Markesot dalam buku ini, Siapa Sebenarnya Markesot? adalah penulisnya itu sendiri. Atau siapa pun di antara manusia yang sekarang sedang belajar dan terus mencari kebenaran tanpa perlu sekali pun merasa paling benar sendiri atas persepsinya tentang jalan menuju Tuhan itu sendiri.
Dan memang sebagai manusia kita dituntut terus menerus mencari kebenaran. Dengan mencari kebenaran, berarti kita menggunakan daya berpikir kita. Itu artinya kita belajar. Karena kita belajar kemungkinan salah dan benar adalah hal yang memungkinkan selalu kita lakukan. Karena itu, pesan bahwa jalan merasa paling benar di antara kemungkinan kebenaran lain adalah hal yang perlu jadi tameng kita dalam beragama.
Kesadaran demikian menunjukkan bahwa kemanusiaan kita masih sehat dan jauh dari sifat menang sendiri dalam perjalanan manusia mencari kebenaran. Sebagai penutup, kita coba kutip tameng yang biasa Markesot pakai ini:
“Jangan menagih saya hal kebenaran karena kebenaran milik Allah. Hanya ada di sisi-Nya atau di genggaman-Nya. Kita dan saya hanya diciprati sangat sedikit. Kewajiban saya dan kita hanyalah setia berproses mencarinya, bukan harus mencapainya.”
Sow, gimana perjalanan Anda kini menjadi manusia, Kisanak?


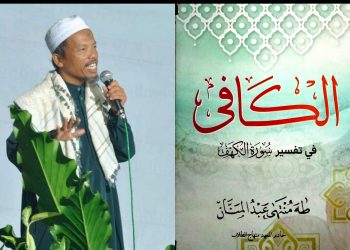










Discussion about this post